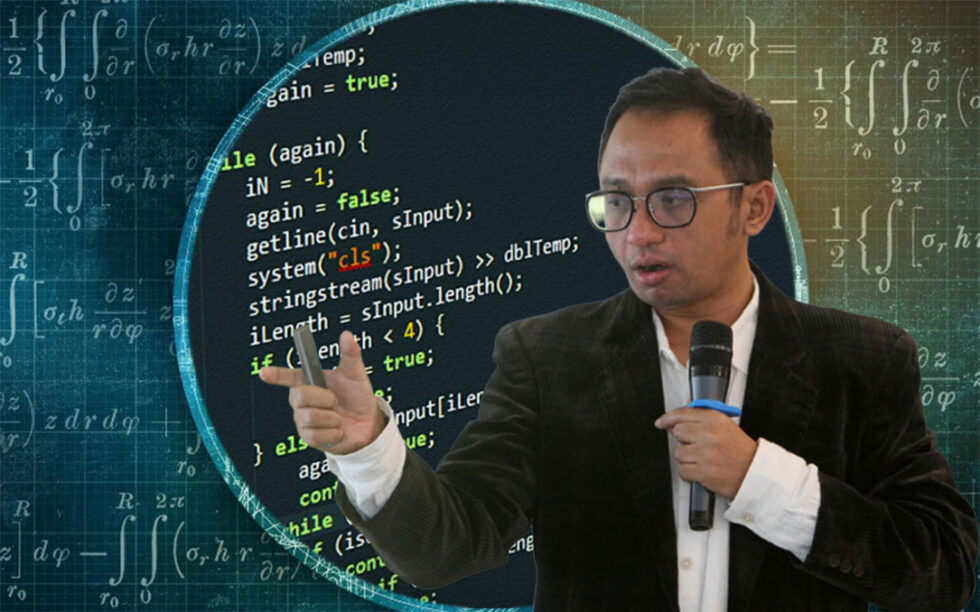
Dorongan regulator dan industri perbankan menuju data-driven decision making selama beberapa tahun terakhir memang memperkuat efisiensi, akurasi mitigasi risiko, dan stabilitas sistem keuangan. Namun di balik kemajuan tersebut, ada paradoks yang jarang dibicarakan, yakni algoritma yang semakin canggih justru berpotensi mempersempit ruang inklusi keuangan, terutama di negara seperti Indonesia yang struktur ekonominya sangat bertumpu pada sektor informal.
Pakar AI dan ekonomi digital yang juga piawai dalam hal AI and risk management compliance Tuhu Nugraha Dewanto menyebut fenomena ini sebagai ‘Algorithmic Malthusianism’—ketika algoritma kredit melihat masa depan hanya dari data masa lalu yang sempit. Dalam perbincangan dengan Deddy H. Pakpahan dari digitalbank.id, dia menjelaskan mengapa bank di Indonesia membutuhkan pendekatan berbeda melalui Small Language Models (SLM) dan pemanfaatan QRIS sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) untuk membangun sistem skor kredit yang lebih adil, relevan, dan berdaulat. Berikut petikan perbincangannya:
Dalam beberapa kesempatan Anda menyebut ada paradoks di balik dorongan data-driven decision making di industri perbankan. Bisa jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Sebenarnya kita saat ini sedang berada dalam situasi di mana efisiensi meningkat, mitigasi risiko membaik, tetapi pada saat yang sama inklusi keuangan justru berpotensi terhambat. Algoritma kredit semakin canggih, tetapi ia melihat masa depan hanya dari data historis yang sempit. Apa yang tidak tercatat dianggap risiko. Apa yang di luar pola lama dianggap ancaman. Inilah yang saya sebut sebagai ‘Algorithmic Malthusianism’.
Anda menyamakan ini dengan teori Malthus, kenapa?
Karena sama seperti Malthus yang mengira pertumbuhan manusia akan selalu dibatasi sumber daya tanpa memperhitungkan inovasi, algoritma kredit juga menganggap kapasitas bayar seseorang dibatasi oleh data masa lalu yang tidak lengkap. Ia tidak memberi ruang pada kreativitas ekonomi, mobilitas sosial, dan dinamika penghasilan yang nyata terjadi di dalam masyarakat.
Apa dampak paling berbahaya dari cara pandang algoritma seperti ini?
Bila algoritma itu yang dipakai, AI mulai mengunci mobilitas sosial bahkan sebelum mobilitas itu terjadi. Orang-orang yang sebenarnya potensial tidak pernah diberi kesempatan karena jejak datanya tidak sesuai template. Regulasi yang mendorong scoring berbasis data tanpa konteks lokal bisa mempercepat eksklusi finansial.
Tapi dari sisi regulator, model besar seperti LLM justru dianggap penting untuk stabilitas, audit, dan prudential banking. Apakah itu salah?
Tidak salah. Justru saya bilang sangat masuk akal dari perspektif regulator. Model besar memberi konsistensi, auditabilitas, dan perlindungan terhadap risiko sistemik. Ia membantu menekan NPL dan menjaga stabilitas. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketika pendekatan itu diterapkan tanpa kemampuan membaca sinyal ekonomi lokal yang tidak formal.
Pada titik itu Anda melihat QRIS punya peran strategis?
Betul. QRIS bukan sekadar alat bayar. Dengan lebih dari 50 juta merchant, ia adalah real-time economic signal yang luar biasa kaya. Banyak pelaku ekonomi informal hanya punya dompet digital, tidak punya rekening bank. Data QRIS sering kali menjadi satu-satunya jendela valid untuk membaca kesehatan arus kas mereka.
Bila algoritma itu yang dipakai, AI mulai mengunci mobilitas sosial bahkan sebelum mobilitas itu terjadi. Orang-orang yang sebenarnya potensial tidak pernah diberi kesempatan karena jejak datanya tidak sesuai template. Regulasi yang mendorong scoring berbasis data tanpa konteks lokal bisa mempercepat eksklusi finansial.
Mengapa model kredit modern yang dipakai negara-negara Barat gagal membaca realitas Indonesia?
Karena sebagian besar model itu lahir dari lingkungan WEIRD—Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Kita mengimpor algoritma yang dibangun dari realitas sosial ekonomi yang rapi dan terdokumentasi. Sementara ekonomi Indonesia cair, informal, berbasis ritme harian UMKM, dan sering tidak tercatat secara formal.
Jadi ketika “tidak ada data”, algoritma langsung menilai “risiko tinggi”, itu yang terjadi saat ini?
Tepat sekali. Padahal di Indonesia, tidak adanya data formal sering kali hanya karena sistem pencatatan yang tidak sempurna, bukan karena orangnya tidak mampu bayar. Di sinilah muncul digital stigma—bias yang bukan berasal dari perilaku nasabah, tetapi dari ketidakcocokan model dengan realitas.
Lalu mengapa Anda menawarkan SLM sebagai solusi, bukan LLM yang lebih canggih?
Karena masalahnya bukan ukuran model, tetapi kedalaman konteks. SLM jauh lebih ringan, modular, hemat biaya, hemat energi, dan bisa difokuskan pada fitur yang benar-benar relevan seperti perilaku e-wallet, ritme transaksi harian, pola QRIS seperti velocity, ticket size, dan recurrence. Itu jauh lebih representatif dibanding credit history tradisional untuk segmen ini.
QRIS bukan sekadar alat bayar. Dengan lebih dari 50 juta merchant, ia adalah real-time economic signal yang luar biasa kaya. Banyak pelaku ekonomi informal hanya punya dompet digital, tidak punya rekening bank. Data QRIS sering kali menjadi satu-satunya jendela valid untuk membaca kesehatan arus kas mereka.
Apa yang membuat tiga variabel QRIS itu begitu penting?
Ketiganya menangkap denyut ekonomi real-time. Seberapa sering transaksi terjadi, berapa nilai rata-ratanya, dan seberapa konsisten polanya. Itu langsung mencerminkan stabilitas arus kas. Untuk pelaku informal, ini jauh lebih akurat daripada riwayat kartu kredit yang mereka bahkan tidak miliki.
Anda juga menyebut konsep ethics of possibility. Maksudnya?
Algoritma tidak lagi menghukum karena “kurang data”, tetapi membuka ruang bagi banyak kemungkinan. Ia tidak hanya menilai risiko, tetapi juga memetakan potensi.
Kombinasi SLM dan QRIS Anda sebut bisa membangun sovereign credit infrastructure. Bisa dijelaskan?
Kita membangun sistem penilaian risiko yang tidak bergantung pada asumsi ekonomi Barat. Algoritma credit scoring perbankan kita terlalu Barat untuk menilai Indonesia. Dengan data publik nasional seperti QRIS dan model lokal seperti SLM, kita punya arsitektur skor kredit yang sesuai dengan realitas ekonomi Indonesia. Ini soal kedaulatan algoritma dan kedaulatan data.
Anda menyinggung Brasil dengan PIX dan Kenya dengan M-Pesa. Apa pelajaran terpentingnya?
Keberhasilan mereka bukan karena menyalin model Barat, tetapi karena membangun dari realitas mereka sendiri. Data transaksi mikro menjadi fondasi kredit mikro nasional. Indonesia punya peluang yang sama kuatnya melalui QRIS.
Apa yang perlu dilakukan regulator agar ini bisa terealisasi?
OJK dan BI bisa mendorong modular scoring, sandbox khusus SLM, serta integrasi data alternatif. Perlu ada kebijakan yang secara eksplisit memihak pengembangan SLM dan DPI, seperti India dengan Aadhaar dan UPI.
Kita membangun sistem penilaian risiko yang tidak bergantung pada asumsi ekonomi Barat. Algoritma credit scoring perbankan kita terlalu Barat untuk menilai Indonesia. Dengan data publik nasional seperti QRIS dan model lokal seperti SLM, kita punya arsitektur skor kredit yang sesuai dengan realitas ekonomi Indonesia. Ini soal kedaulatan algoritma dan kedaulatan data.
Keunggulan bank masa depan tidak ditentukan oleh apakah bank itu punya teknologi paling canggih, tetapi lebih pada bank yang algoritmanya paling memahami realitas masyarakatnya. Ketika algoritma berhenti menjadi pagar dan mulai menjadi jembatan, di situlah inklusi keuangan benar-benar terjadi. ■
Digionary:
● Data-driven decision making: Pengambilan keputusan berbasis analisis data, bukan intuisi semata.
● Algorithmic Malthusianism: Kecenderungan algoritma melihat masa depan hanya dari data masa lalu yang sempit sehingga membatasi peluang baru.
● Inklusi keuangan: Upaya membuka akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang belum terlayani bank.
● LLM (Large Language Model): Model AI berskala sangat besar dengan kebutuhan data dan komputasi tinggi.
● SLM (Small Language Model): Model AI berukuran kecil, modular, hemat biaya, dan bisa disesuaikan dengan konteks lokal.
● Digital Public Infrastructure (DPI): Infrastruktur digital publik milik negara yang bisa dimanfaatkan luas, seperti QRIS.
● QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard): Standar kode QR nasional untuk transaksi pembayaran digital.
● QRIS velocity: Kecepatan atau frekuensi transaksi QRIS dalam periode tertentu.
● Ticket size: Nilai rata-rata setiap transaksi yang dilakukan pengguna.
● Transaction recurrence: Pola pengulangan transaksi yang menunjukkan konsistensi aktivitas ekonomi.
● WEIRD: Singkatan dari Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic—konteks negara asal banyak model algoritma.
● Digital stigma: Bias algoritma yang menganggap ketiadaan data formal sebagai risiko tinggi.
● Marketing myopia: Ketidakmampuan melihat peluang pasar besar karena terjebak pola pikir lama.
● Prudential banking: Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko perbankan.
● NPL (Non-Performing Loan): Kredit bermasalah atau gagal bayar.
● Sovereign credit infrastructure: Sistem penilaian kredit yang dibangun dari data dan model lokal yang berdaulat.
● Ethics of possibility: Pendekatan etis yang melihat potensi, bukan hanya risiko, dalam penilaian kredit.
● Ekonomi informal: Aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal dalam sistem perbankan.
● Alternative data: Data non-tradisional (e-wallet, QRIS, transaksi harian) untuk menilai kelayakan kredit.
● Modular scoring: Sistem skor kredit yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai sumber data.
#AIIndonesia #SLM #LLM #QRIS #InklusiKeuangan #DigitalBank #FintechIndonesia #AlgoritmaKredit #DPIIndonesia #EkonomiInformal #UMKM #DataDriven #SovereignAI #KedaulatanDigital #CreditScoring #OJK #BankIndonesia #EthicsofPossibility #DigitalStigma #TeknologiKeuangan





